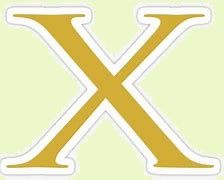Bersua Pelaku di Penjara
Pada malam Jumat, 21 November 1974, kediaman pasutri H. Sulaiman dan Siti Haya di Bojongsari, Kabupaten Bekasi, disatroni perampok. Tak hanya kehilangan harta, pasutri korban itu juga meregang nyawa.
Mengutip Tim Lindsey dalam artikel “Reconsidering Reform: The Supreme Court and Indonesia’s Extraordinary Legal Measure” yang termaktub dalam buku Crime and Punishment in Indonesia, seorang saksi yang mengaku ikut berusaha melarikan korban ke rumahsakit, mendengar bahwa H. Sulaiman dalam keadaan sekarat membisikkan nama Sengkon dan Karta.
“Nama Sengkon (dan Karta) yang merupakan petani setempat diduga dibisikkan sang korban yang sedang sekarat saat hendak dibawa ke rumahsakit. Sebuah sandal miliknya (Sengkon) juga ditemukan dekat tempat kejadian perkara,” tulis Lindsey.
Atas dasar itulah kemudian aparat kepolisian yang menginvestigasi kasusnya menciduk Sengkon dan Karta, lalu menjadikan keduanya tersangka. Dalam interogasi, Sengkon dan Karta membantah tapi dipaksa mengaku sebagai pelakunya.
“Polisi menangkap Sengkon bin Jakin dan Karta Al (alias) Karung Al Encep bin Salam dengan tuduhan kasus tersebut. Keduanya menolak mengaku sebagai pelaku. Setelah mengalami siksaan polisi, akhirnya keduanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP, red.),” tulis Yerry Wirawan dalam artikel “Kekacauan Hukum di Indonesia: Kasus Sengkon dan Karta” di buku Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda.
Meski begitu, baru pada Oktober 1977 Sengkon dan Karta menghadapi persidangan di PN Bekasi. Dari beberapa saksi yang dihadirkan, tiga di antaranya menguatkan pembelaan kedua terdakwa dengan mengatakan di waktu kejadian, Karta sedang terbaring sakit.
Nahas, ketua majelis hakim Djurnetty Soetrisno menolak pernyataan saksi dan pembelaan kedua terdakwa. Djurnetty lebih mendasarkan keputusannya pada BAP kepolisian dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sengkon dan Karta akhirnya dijatuhi vonis penjara. Sengkon dihukum 12 tahun, sementara Karta divonis lebih ringan, 7 tahun penjara.
Melalui kuasa hukumnya, Sengkon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung namun ditolak. Sedangkan Karta memilih pasrah menerima vonisnya.
“Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1/KTS/Bks/1977 yang dikuatkan oleh Putusan Tinggi Bandung Nomor 38/1978/Pid/PTS, Sengkon (tetap) dihukum selama 12 tahun penjara dan Karta dihukum selama 7 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan dan perampokan,” ungkap D. Y. Witanto dalam Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan.
Sengkon dan Karta pun makin pasrah. Bertahun-tahun mereka mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP) Cipinang.
Pada medio 1980, tetiba saja ada seorang tahanan lain bernama Gunel yang dibui karena kasus pencurian. Beberapa sumber lain menyebutkan namanya “Genul”, dan disebutkan pula ia masih kerabat dari Sengkon. Gunel merasa iba pada Sengkon pasalnya kondisi Sengkon sedang parah terkena TBC. Gunel mengaku bahwa dia dan teman-temannyalah yang merampok dan membunuh H. Sulaiman dan Siti Haya istrinya.
“Dengan jujur dan merasa berdosa ia minta maaf kepada Sengkon yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Pengakuan Gunel itu akhirnya diketahui media massa,” tulis advokat Bachtiar Sitanggang dalam kolom hukum di majalah Mimbar Kekaryaan ABRI edisi Maret 1997, “Hakikat Peninjauan Kembali Atas Suatu Perkara Pidana”.
Berkat pemberitaan media massa besar-besaran, DPR, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung (MA) pun “turun tangan”. Gunel dan teman-temannya lantas kembali disidang di PN Bekasi pada Oktober 1980 atas kasus perampokan dan pembunuhan H. Sulaiman dan Siti Haya.
“Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 6/1980/Pid/PN Bks dan Putusan Nomor 7/1980/Pid/PN Bks, Gunel, Elly, dkk dinyatakan terbukti bersalah,” sambung Witanto.
Gunel sendiri menerima vonis 12 tahun penjara. Sementara, Sengkon dan Karta dipulihkan statusnya dengan menghidupkan kembali mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang sempat mati suri.
Dengan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980, Sengkon dan Karta diperiksa ulang dan dinyatakan tidak bersalah. Lalu karena alasan kesehatan, pada 3 November 1980 Sengkon dan Karta akhirnya menghirup udara bebas untuk segera dilakukan perawatan intensif, walau penetapan resmi pembebasannya baru keluar pada 4 November 1980.
Kepolisian Negara Republik Indonesia kini sudah berumur 78 tahun. Umur yang sudah terbilang matang untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menjaga ketertiban dari berbagai macam kriminalitas juga turut menjadi tugas polisi.
Sudah banyak kasus-kasus besar yang ditangani polisi. Hasil survei Kompas periode Juni 2024 menunjukkan citra beberapa lembaga hukum, seperti Polri, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih positif dibandingkan dengan survei sebelumnya. Citra Polri naik 1,6 persen dan menduduki posisi kedua setelah TNI.
Walau demikian, citra polisi yang mulai membaik semenjak kasus penembakan Brigadir J hingga menyeret nama Ferdy Sambo kembali dipertanyakan oleh publik. Rentetan kasus yang mempertanyakan keprofesionalitasan polisi kian menjadi bahan perbincangan. Di antaranya adalah kala Pegi Setiawan alias Perong bebas dari status tersangka pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat setelah putusan sidang praperadilan dibacakan Hakim Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (8/7/2024). Penetapan tersangka Pegi dianggap bermasalah dan tidak sah secara hukum.
PERJALANAN kasus Pegi Setiawan boleh dibilang cukup melelahkan, bahkan kasus yang terjadi sejak delapan tahun yang lalu hingga sekarang masih dihiasi kabut, siapa sebenarnya yang membunuh dan memperkosa Vina dan Eky, dua sejoli yang matinya sangat mengenaskan. Pegi yang sekarang dalam jeruji besi atau Pegi lain yang masih berkeliaran di luar jangkauan hukum, entah!
Dari gambaran kasus yang ada sebetulnya bukan kasus yang sulit dilacak karena tempat kejadian perkara di wilayah terbuka yaitu, jalan raya dan bukan satu lawan satu, akan tetapi dengan melibatkan orang banyak. 11 orang yang tergabung dengan geng motor untuk mengeksekusi dua orang korban Vina dan Eky (keduanya meninggal). Dari catatan peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan ke-2 dari pemeriksaan sebelumnya (delapan tahun yang lalu) yang hanya memproses 8 (delapan) pelaku dan sisanya 3 orang dianggap DPO oleh Polres Cirebon.
Dari PR 3 orang ini yang dinyatakan DPO, ternyata menjadi bola panas, tiba tiba kasus yang sudah cenderung adem kembali menggeliat bukan pada sisi pemerkosaannya yang tergolong “biadab” akan tetapi aktor di balik itu yang sudah di tangkap Polisi, yaitu Pegi Setiawan si tukang bangunan. Dan menurut versi penyidik, salah satu alasan penangkapan Pegi karena yang bersangkutan mengganti nama di tempat kontrakannya di Bandung, aneh!
Dalam hukum acara seseorang ditetapkan sebagai Tersangka bukan pada mengganti indentitas, akan tetapi terpenuhinya bukti permulaan yang cukup Pasal 17 KUHAP. Karena dilapangan hukum seseorang mengganti nama dari nama sebenarnya kenama samaran tidak digolongkan kejahatan sepanjang perbuatan itu ditujukan bukan untuk kejahatan yang merugikan orang lain.
Sehingga wajar pernyataan penyidik dianggap tidak sesuai ketentuan hukum acara. Sehingga wajar pula penyidik dianggap gamang dalam menghadapi kasus ini.
Selain minimnya alat bukti yang mengarah ke Pegi Setiawan, juga dalam catatan DPO bukan nama Pegi Setiawan akan tetepi Pegi Perong. Dua nama yang jauh beda di belakangnya. Selain nama juga wajah yang diyakini Pegi Setiawan berbeda dengan Pegi Cianjur yang banyak dimunculkan nitizen. Pegi Cianjur adalah bertato dan bertampang keren, layaknya orang berada, bukan seperti Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai tukang bangunan dari keluarga sederhana, tentunya sulit disandingkan. Apalagi yang namanya Geng Motor, tentunya bukan anak-anak muda sembarangan yang berlatar belakang keluarga yang dari sisi ekonomi di bawah garis kecukupan. Geng motor biasanya datang dari keluarga berada dan yang berkecukupan dari sisi ekonomi.
Lalu dari keadaan ini terdapat kecenderungan penyidik salah tangkap. Korban Salah Tangkap yang menginspirasi Penegakan Hukum pada Sengkon dan Karta (Indonesia) serta Jean Calas di Prancis.
Kasus salah tangkap yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus Sengkon dan Karta yang terjadi tahun 1974. Dalam catatan putusan, Sengkon dan Karta pada tahun 1974 dituduh merampok dan membunuh pasangan suami isteri, Alm Sulaiman dan Siti Haya. Dalam putusan keduanya dinyatakan bersalah dan masing-masing dijatuhi hukuman 12 tahun untuk Sengkon dan 7 tahun untuk Karta.
Dalam perjalanan panjangnya melakoni kasus itu Sengkon dan Karta yang menolak dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan, namun keduanya tidak berdaya karena Penyidik kala itu punya tips untuk mencapai tujuannya yaitu, menekan dengan cara verbal dan fisik.
Selama di dalam penjara Sengkon dan Karta menemui sang pembunuh, bernama Genul dan tidak lain adalah orang yang sama-sama di satu sel. Singkat cerita, akhirnya berkat terobosan Mahkamah Agung pada tahun 1981 di bawah pimpinan Prof Oemar Seno Aji SH telah membuka kran baru dalam dunia peradilan yang disebut PK (Peninjauan Kembali) karena kala itu Peninjauan Kembali (PK) tidak dikenal dan putusan kasasi adalah putusan terakhir yang disebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.
Ada yang menarik dalam proses hukum Sengkon dan Karta, setelah diketahui telah terjadi salah tangkap, melalui usul Menteri Kehakiman ke Mahkamah Agung agar terlebih dahulu Sengkon dan Karta dikeluarkan dari tahanan atau istilah waktu itu skorsing yang disepakati oleh Jaksa Agung. Dan sambil menunggu upaya hukum yang belum ada aturannya Sengkon dan Karta bebas. Karena para petinggi di bidang hukum merasa, kasus Sengkon dan Karta adalah aib dalam dunia peradilan yang sesat.
Berkat terobosan Ketua MA, terbit suatu langkah hukum baru berupa “herziening“ atau dikenal dengan istilah PK (Peninjauan Kembali). Akhirnya berkat Peninjauan Kembali (PK) Sengkon dan Karta bebas dari hukuman 12 dan 7 tahun. Dan keduanya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana Perampokan dan Pembunuhan.
Dari penggalan cerita di atas, kita dapat merenung, betapa sejarah kelam Sengkon dan Karta dalam mencari keadilan sangat dijunjung tinggi oleh Punggawa hukum kala itu, jawabannya sederhana mereka mengedepankan hati nurani pada sisi keadilan, bukan seperti sekarang yang mengedepankan kepentingan tertentu.
Dan dari peristiwa kelam wajah hukum kita pada nasib Sengkon dan Karta, seorang buruh tani yang begitu mendapat simpatik masyarakat dan Petinggi hukum, juga mengingatkan kita pada pusaran sejarah Jean Calas di Prancis pada abad 17 yang menyerupai Sengkon dan Karta berupa peristiwa hukum salah tangkap. Jean Calas, 13 Oktober 1761 (catatan; Tribune Manado, 25 Maret 2024) namun dari banyak penelusuran peristiwa kelam sejarah hukum Prancis, dimulai tahun 1762.
Calas seorang Ayah yang dituduh telah membunuh anaknya Marc-Antoine dengan tuduhan masalah Agama. Karena Calas yang Protestan tidak mau anaknya memilih keyakinannya menjadi Katolik. Atas tuduhan itu ia dihukum dengan cara yang sangat keji. Namun beberapa waktu lalu diketahui si anak meninggal karena bunuh diri dengan cara Gantung Diri. Sehingga Jean Calas yang sudah dieksekusi dan meninggal oleh Negara, dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan secara anumerta sebagai bentuk pengakuan (bersalah) pemerintah atas kesewenang-wenangan di zamannya.
Dalam sistem peradilan Prancis yang mengandalkan kekuasaan penguasa dan hukum gereja kala itu, hukum menjadi tidak terukur. Penegakan hukum hanya menjadi alat pada tataran kepentingan penguasa bukan pada tujuan dari hukum itu sendiri yang tidak berpegang kepada azas praduga tak bersalah (presumption of innocence), artinya seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.
Inspirasi Kebangkitan Hukum
Calas menginspirasi kebangkitan hukum di negaranya yang sewenang wenang dengan mengedepankan kepentingan penguasa dan gereja, menjadi hukum yang modern dan mengikis kekuatan hukum gereja menjadi hukum tertulis (kodifikasi). Kesalahan yang terjadi di Prancis membuat cambuk dalam memperbaharui kehidupan dalam masalah penegakan hukum yang berlaku khususnya masalah-masalah pidana atau di Prancis terkenal dengan kode fenal yang merupakan kodifikasi hukum pidana Prancis.
Dari dua catatan sejarah kelam sisi penegakan hukum baik di Prancis dan di Indonesia nampaknya tidak segaris dalam menyikapinya. Di Prancis keadaan hukum di sana yang menganut sistem Eropa Kontinental terus mengalami perbaikan hukum. Dan beda dengan Indonesia yang terus mengalami kemunduran, utamanya masalah-masalah yang berlaku dalam tindak pidana. Isu salah tangkap bukan lagi wilayah yang haram untuk diproses.
Peristiwa Sengkon dan Karta bukan lagi menjadi cambuk untuk berbenah, akan tetapi menjadi bagian yang terus berulang. Harusnya pihak kepolisian khususnya di Serse dapat berbenahi untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip kesetaraan yang baik di mata hukum.
Hentikan praktek pratek yang bersifat melawan hukum. Karena pada ujungnya masyarakat semakin paham semakin mengerti, apa itu kebenaran. Karena kebenaran bukan daging anjing yang ditutupi menjadi daging ayam yang layak dimakan.
Dugaan Peradilan Semu Ditangan Penyidik
Dalam proses perkara pidana sebelum seseorang diadili, terlebih dahalu di BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik dalam rangka mencari alat bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Seiring berjalannya waktu penyidik bukan lagi berperan sebagai penyidik, akan tetapi telah mengambil domeinnya Pengadilan yaitu, melakukan Penyumpahan kepada para saksi dan ahli.
Awalnya langkah ini hanya untuk mengantisipasi kalau kalau saksi tidak dapat datang karena tempat yang jauh namun, seiring berjalannya waktu langkah itu di diduga telah disalahgunakan dan dijadikan model dalam penyidikan yaitu, dengan cara hampir semua saksi disumpah dengan alasan takut tidak datang saat sidang Pengadilan. Demikian juga untuk ahli, sama di sumpah dalam tahap penyidikan. Namun ternyata cara ini sangat efektif dalam memperlancar Proses persidangan utamanya dalam menyiasati jalannya persidangan. Karena biasanya saksi dan ahli yang disumpah jarang dibacakan karena dianggap sudah sempurna keterangannya. Padahal saksi-saksi yang telah diperiksa dan disumpah belum tentu benar keterangannya, demikian juga Ahli.
Jadi BAP saksi dan ahli sudah disumpah oleh penyidik pada tahapan sidang pengadilan hanya mengamini apa yang sudah tertuang dalam BAP dalam tahap penyidikan. Dan biasanya kalau kita Protes karena ada saksi yang diduga memberi keterangan palsu juga Ahli, Hakim dengan segala kekuasaannya mengabaikan hak-hak pengacara.
Dalam suatu perkara yang pernah saya tangani, saksi itu dalam keterangannya kaitan kasus yang menjerat klien adalah saksi palsu. Namun karena sudah disumpah apapun protes kita akan diabaikan oleh hakim.
Pertanyaannya, kenapa saksi yang telah disumpah oleh (Oknum) penyidik tidak dapat dipertanggungjawabkan kehadirannya di muka sidang, karena telah disumpah, sehingga yang bersangkutan tidak wajib datang dan memberi keterangan di Pengadilan. Padahal alasan pokoknya karena takut saksi akan kena sumpah palsu. Sebab memberi keterangan di Pengadilan yang mempunyai tatacara sesuai hukum acara yang berlaku.
Langkah pertama, sebelum memberi kesaksian Saksi akan disumpah terlebih dahalu dengan menyertakan kitab suci dan Menyebut:
Demi ALLAH Saya …. Bagi yang beragama Islam. Atas nama Tuhan Saya…. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen. Dan seterusnya.
Akibat dari sumpah itu apabila benar palsu maka saksi akan kena Pasal 242 KUHP yang diancam pada pasal ayat 1 tujuh (7) tahun dan sembilan (9) tahun. Dengan model penyidikan seperti ini kita juga kadang kaget, kok orang yang tidak ada sangkut pautnya jadi saksi dengan disumpah di hadapan penyidik. Dan menurut sumpah di depan penyidik kalaupun kita tahu akan sulit saksi yang diduga palsu untuk dilaporkan.
Pertama, keterangan seorang saksi menurut KUHAP hanya sah apabila dilakukan di depan sidang, hal ini terurai dengan jelas di pasal 185 KUHAP.
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
Jadi sahnya seorang saksi sebagai alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah, saksi yang memberi keterangan di depan sidang pengadilan, bukan didepan penyidik.
Selain itu di pasal 242 KUHP ditegaskan, bahwa dari unsurnya makna 242 KUHP tentang sumpah palsu.
-Keterangan itu harus bohong atau benar.
-Keterangan harus dibawah sumpah yang merujuk kepada pasal 185 KUHAP.
-Keterangan harus didepan pengadilan
-Sudah diperingatkan oleh Majelis Agar memberi keterangan yang benar bukan yang bohong. Barangkali dari banyak kejadian, peran penyidik yang mengambil domain Hakim perlu dipikirkan oleh Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung untuk tidak memberi peran terkait sumpah terhadap para saksi dan ahli, karena dampaknya akhir-akhir ini menjadi roll model yang sangat membahayakan dalam penegakan hukum. Biarkan wilayah penyumpahan hanya menjadi domain pengadilan, bukan kepolisian.
Mari bercermin dari 2 kasus di atas Sengkon dan Karta serta Jeans Colas yang telah mewarnai dunia hukum ke arah yang baik karena kesalahan harus menjadi contoh untuk kebaikan, bukan sebaliknya.
Ditulis oleh : C Suhadi SH MH, Koordinator Team Hukum Merah Putih.
Ilustrasi sidang Sengkon dan Karta korban salah tangkap yang dituduh merampok dan membunuh. Foto/Istimewa
Kisah Sengkon dan Karta mungkin masih teringat jelas bagi sebagian masyarakat Indonesia. Keduanya merupakan korban
yang sempat dituduh melakukan tindak perampokan dan pembunuhan.
Baru-baru ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly turut berkomentar dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Rizky Rudiana alias Eky di Cirebon pada 2016.
Ia berharap penanganan perkara pidana bisa ditangani dengan baik, tak seperti dalam kejadian Sengkon dan Karta yang terjadi puluhan tahun lalu. Lantas, apa itu sebenarnya kasus yang menimpa Sengkon dan Karta sehingga menjadikannya kisah tak terlupakan?
Berikut ini ulasannya:
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
DUGAAN salah tangkap kembali terjadi pada kasus perampokan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan pada Selasa (30/7/2024) dengan terdakwa Hajidin (47). Seorang saksi yang dihadirkan justru mengaku sebagai pelaku aslinya.
Hajidin disidang dalam kasus perampokan terhadap korban, Wagirin, di Mesuji Makmur, OKI, medio Januari 2024. Hajidin ditangkap aparat kepolisian sebulan berselang dan kini duduk di kursi pesakitan. Tetapi kemudian dalam persidangan, Sutikno (38, dalam beberapa sumber dituliskan Sutekno) yang hadir sebagai saksi, justru memberi pengakuan bahwa dialah yang merampok Wagirin.
“Saya pribadi meminta maaf kepada keluarga Pak Hajidin. Karena ulah saya, Pak Hajidin menanggung permasalahan ini,” aku Sutikno, disitat IDN Times, Jumat (2/8/2024).
Polres OKI yang menetapkan tersangkanya tetap meyakini Hajidin pelakunya. Sementara, pihak keluarga terdakwa berharap majelis hakim membebaskannya dari segala dakwaan.
Dugaan salah tangkap memang kerap kali terjadi. Sebelumnya, Pegi Setiawan juga jadi korban salah tangkap atas “Kasus Vina Cirebon”. Belakangan, dengan desakan warganet, Pegi dibebaskan pasca-memenangkan gugatan praperadilan pada awal Juli 2024.
Sejarah juga pernah mencatat kasus salah tangkap yang menggemparkan pada 1970-an, yakni kasus perampokan dan pembunuhan seorang pedagang bernama H. Sulaiman di Bekasi dengan terpidana Sengkon dan Karta. Jika kasus dugaan salah tangkap Hajidin masih berproses di persidangan, pengungkapan kebenaran akan Sengkon dan Karta baru terjadi saat keduanya sudah bertahun-tahun mendekam di penjara.
Kisah Pilu Sengkon dan Karta
Sengkon dan Karta merupakan dua petani biasa asal Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Namun, suatu hari di 1974, keduanya ditangkap karena tuduhan melakukan aksi perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan suami-istri, Sulaiman-Siti Haya.
Merasa tidak bersalah, Sengkon dan Karta awalnya menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Namun, mereka dikatakan mendapat ancaman dan siksaan, sehingga terpaksa menyerah.
Beralih menuju pengadilan, Hakim Djurnetty Soetrisno memberi vonis 12 tahun penjara untuk Sengkon dan 7 tahun untuk Karta. Keduanya pun dijebloskan ke dalam jeruji besi.
Beberapa waktu berselang, Tuhan akhirnya menunjukkan titik keadilan. Saat berada di LP Cipinang, Sengkon dan Karta bertemu dengan seorang tahanan lain bernama Genul.
Pengakuan sosok Genul ini akhirnya membuka tabir hitam. Ia mengaku sebagai pembunuh Sulaiman-Siti, sehingga tuduhan bagi Sengkon dan Karta adalah kesalahan.
Setelah melewati lika-liku panjang, akhirnya Genul dan komplotannya dinyatakan sebagai tertuduh utama kasus pembunuhan Sulaeman-Siti. Ia dituntut penjara selama 12 tahun.
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan narapidana kasus Pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap kepolisian dalam peristiwa di Cirebon pada 2016 silam itu. Terdakwa dengan vonis 8 tahun penjara dan kini sudah bebas tersebut bersuara setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat. Saat peristiwa terjadi, kata dia, dirinya tengah berada di rumah.
"Saya sedang ada di rumah bersama kakak dan paman saya,"ungkapnya saat kepada wartawan di Cirebon, Sabtu petang, 18 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saka bercerita, sesaat sebelum ditangkap, dirinya disuruh sang paman untuk mengisi bahan bakar motor di stasiun pengisian. Saat dirinya kembali, sudah ada polisi yang menunggu. Tanpa penjelasan, Saka kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Cirebon Kota. Tak hanya salah tangkap, ia juga mendapat kekerasan fisik agar mengakui perbuatannya.
"Saya dipukulin, ditendang, disiksa segala macam. Bahkan saya juga sampai disetrum sama bapak Polisi semua. Karena enggak kuat disiksa, akhirnya saya terpaksa mengakui bahwa saya ikut dalam kasus pembunuhan itu. Terus disuruh mengakui yang tidak saya lakukan (pembunuhan)," kenangnya.
Padahal, menurut pengakuan Saka, dirinya tidak mengenal korban dan tersangka lain yang membunuh Eky dan Vina. Bahkan, Saka mengaku belum pernah bertemu dengan tiga DPO yang dirilis oleh Polda Jabar belum lama ini. Saka juga menegaskan dirinya bukan anggota geng motor. Sebab itu, ia mengaku menjadi korban salah tangkap dalam peristiwa pembunuhan Eky dan Vina.
"Saya bukan anggota geng motor, saya enggak punya motor sama sekali,"ucapnya.
Kasus salah tangkap bukanlah hal langka. Salah satu yang paling fenomenal adalah kasus Sengkon dan Karta. Dilansir dari Majalah Tempo, mereka adalah petani dari Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditangkap atas tuduhan perampokan dan pembunuhan pasangan suami-istri, Sulaiman-Siti Haya, warga Desa Bojongsari.
Pada 1977, Pengadilan Negeri Bekasi memvonis Sengkon 13 tahun penjara dan Karta 7 tahun. Keduanya disebut telah mengaku membunuh, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan polisi. Sengkon dan Karta pun dijebloskan ke penjara di Lapas Cipinang, Jakarta, setelah sebelumnya mendekam di penjara Bekasi.
Di Cipinang inilah mereka bertemu dengan Genul, keponakan Sengkon yang dibui lantaran kasus pencurian. Fakta yang sebenarnya pun terungkap. Genul mengaku bahwa dirinyalah pembunuh Sulaiman dan Siti. Setelah pengakuannya tersebut, Genul diadili dan divonis 12 tahun penjara karena terbukti membunuh.
Namun, setelah Genul diadili bukan berarti Sengkon dan Karta lantas dibebaskan. Pada masa itu, lembaga herziening (peninjauan kembali) sudah dibekukan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara pidana tidak bisa ditinjau. Baru setelah Ketua Mahkamah Agung, Oemar Seno Adji membuka kembali lembaga herziening, Sengkon dan Karta dinyatakan bebas murni.
Sayang, penderitaan mereka berdua belum selesai. Selepas keluar dari jeruji, Sengkon dirawat di rumah sakit lantaran tuberkulosisnya makin parah. Sementara Karta, bapak 12 anak, harus menemui kenyataan pahit keluarga yang kocar-kacir. Tanah yang sebelumnya digunakan Karta untuk mencari nafkah telah habis lantaran dijual untuk penghidupan keluarganya dan membiayai diproses pengadilan.
Pada 1982, Karta akhirnya tutup usai setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Sengkon menyusul pada 1988 setelah bertahun-tahun menderita tuberkulosis sekeluarnya dari penjara. Berdekade seterusnya, kasus salah tangkap dan salah sasaran menjatuhkan hukuman terus terjadi.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | MICHELLE GABRIELA
Polisi Salah Tangkap: Kisah Tragis Sengkon dan Karta
Jakarta – Isu polisi salah tangkap kembali mencuat setelah pengakuan Saka Tatal, terdakwa kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tatal membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut dan mengklaim sebagai korban salah tangkap polisi.
Fenomena ini diperparah oleh sejarah kelam polisi dalam salah tangkap, seperti kasus Sengkon dan Karta. Pada 1974, kedua petani asal Bekasi ini ditangkap atas tuduhan merampok dan membunuh pasangan suami istri. Meski menyangkal, mereka dipaksa mengakui kesalahan di bawah kekerasan.
Akibatnya, Sengkon divonis 12 tahun penjara, sedangkan Karta dijatuhi hukuman 7 tahun. Namun, Gunel, narapidana di LPK Cipinang, tiba-tiba mengakui melakukan kejahatan tersebut.
Pengakuan Gunel menjadi bukti baru yang mendorong Mahkamah Agung mengambil tindakan. Pada 4 November 1980, MA menyetujui “penghentian sementara” hukuman Sengkon dan Karta sambil menunggu upaya peninjauan kembali.
Meski dibebaskan, Sengkon menderita tuberkulosis yang dideritanya di penjara. Sementara itu, Karta kehilangan tanah miliknya karena digadai dan dijual istrinya. Setelah keluar dari penjara, ia hidup dalam kemiskinan dan anak-anaknya putus sekolah.
Kasus Sengkon dan Karta menjadi bukti nyata bahwa peradilan dapat berbuat kesalahan. Karta meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 1982, sedangkan Sengkon menyusul pada 1988 karena tuberkulosis.
Sayangnya, kasus salah tangkap terus berulang meskipun telah berdekade berlalu. Pihak kepolisian dan pengadilan dinilai belum belajar dari tragedi Sengkon dan Karta.
Kasus Sengkon dan Karta menyoroti kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam kasus ini, polisi menggunakan kekerasan untuk memaksa pengakuan, dan peradilan tidak memberikan keadilan bagi korban salah tangkap.
Akibatnya, Sengkon dan Karta kehilangan kebebasan dan kehidupan mereka. Kasusnya juga menunjukkan sulitnya mendapatkan keadilan bagi korban salah tangkap, terutama ketika bukti baru muncul setelah mereka dihukum.
Tragedi Sengkon dan Karta seharusnya menjadi pengingat bagi pihak berwenang untuk mereformasi sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup peningkatan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, memastikan ketepatan dalam proses penyelidikan dan persidangan, serta mempermudah proses peninjauan kembali bagi korban salah tangkap.
Dengan demikian, dapat dicegah kejadian serupa terulang kembali dan keadilan dapat ditegakkan bagi semua warga negara.